Spirit NTT, 25 Februari - 2 Maret 2008
MUATAN lokal (mulok) sebagai salah satu unsur muatan Kurikulum 1994 mulai diterapkan sejak tahun 1994. Status mulok sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah (dasar dan menengah)? kemudian diperkuat posisinya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan pada tanggal 8 Juli 2003.
Di dalam UU tersebut, mulok ditetapkan sebagai salah satu dari 10 mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Akan tetapi bagaimana dan apa isi mulok tersebut akan ditentukan kemudian dalam ketentuan peraturan lainnya seperti PP, Kepmen atau SK Dirjen.
Dengan demikian masih terbuka peluang masukan kepada pihak penentu kebijakan dalam rangka penyusunan ini (substansi) muatan lokal dalam Kurikulum 2004. Karena Kurikulum 2004 masih dalam proses, maka pelaksanaan mulok di sekolah tetap berpedoman pada ketentuan Kurikulum 1994 serta peraturan lainnya.
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai masalah yang dihadapi selama kurang lebih 12 tahun penerapan mulok di sekolah,
khususnya dalam aspek kebudayaan (mata pelajaran bahasa daerah) serta mencoba mengajukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam penerapan mulok tersebut. Hasilnya diharapkan menjadi bahan saling tukar informasi dan diskusi bagi upaya pengembangan kurikulum muatan lokal, utamanya yang berkaitan dengan aspek kebudayaan di dalam kurikulum 2004.
Masalah yang dihadapi
Berdasarkan Kurikulum 1994 pihak depdikbud mengeluarkan kebijakan bahwa isi mulok pada masing-masing propinsi dapat berupa mata pelajaran kesenian, keterampilan (bercocok tanam, berternak, mengukir, mengayam, membantik, merajut, mengelas dan keterampilan lainnya), bahasa daerah dan budaya daerah, dan bahasa Inggris untuk SD.
Penentuannya dikaitkan dengan ketersediaan tenaga pengajar, buku pelajaran dan sumber belajar lainnya serta sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Isinya ditentukan oleh daerah, dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat informasi, saran dan masukan dari pemerintah daerah/bappeda, para tokoh masyarakat dan instansi terkait, baik tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten pada wilayah propinsi yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara menetapkan bahwa daerah (Tolaki, Muna dan Wolio)? sebagai muatan utama, sementara materi pilihan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah kecamatan, desa/kelurahan dan sekolah. Ketentuan ini termuat dalam SK Kakanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi tenggara No. 001/123/I/1994, tanggal 2 April 1994.
Selama kurang lebih 10 tahun penerapan mulok tersebut berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah, utamanya yang berkaitan dengan aspek kebudayaan (bahasa daerah) dapat dikemukakan sebagai berikut:
Pertama, dari segi guru yang tidak dipersiapkan sebelumnya sehingga berlaku prinsip tak ada rotan akarpun jadi. Biayanya guru? Mulok (bahsa daerah) adalah guru yang dapat berbahasa daerah berdasarkan pengalaman sehari-hari saja, tetapi tidak menguasai secara teoritis. Bagaimanapun juga bahasa daerah memiliki kaidah dan aturan tata bahasa yang harus dipelajari secara sungguh-sungguh oleh guru. Sistem guru kelas juga merupakan kendala tersendiri. Masalah yang muncul di dalam sistem guru kelas ini adalah bagaimana dengan guru yang tidak menguasai bahasa daerah. Akibatnya guru tidak serius mengajar, terkesan asal-asalan dan akal-akalan, apalagi mata pelajaran ini tidak di-ebtanas-kan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan buku paket serta buku-buku pendukung lainnya.
Kedua, dari segi siswa dengan latar belakang kultural yang berbeda-beda, terutama sekolah di kota dan daerah transmigrasi. Mereka kurang tertarik dengan pelajaran bahasa daerah karena merasa bukan bahasa ibunya, siswa merasa sebagai pendatang, atau tidak dibutuhkan dalam aktivitas kesehariannya. Pihak Kanwil Depdikbud Sulawesi Tenggara hanya mewajibkan tiga bahasa daerah (Tolaki, Muna dan Wolio) padahal di daerah ini terdapat sekitar 30 bahasa lokal yang tersebar di lima kabupaten dan dua kota, dimana antara satu bahasa dengan bahasa lainnya sangat berbeda. Di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau, misalnya, terdapat lebih dari 20 bahasa lokal, namun hanya satu bahasa yang wajib dipelajari, yaitu bahasa Wolio. Ini menjadi masalah besar bagi sekolah yang tak satupun gurunya mengerti bahasa Wolio, apalagi mengajarnya.
Di kota kendalanya lebih rumit lagi, latar belakang etnik siswa di kota beranekaragam dan populasinya hampir seimbang. Artinya, tidak ada yang dominan, lantas bahasa daerah apa yang harus diajarkan. Demikian pula sekolah-sekolah di daerah transmigrasi yang umumnya berasal dari Jawa dan Bali, perlukan mereka belajar bahasa daerah lain.
Ketiga, Pemerintah pun menerapkan kebijakan 'setengah hati' kurang tegas, tidak disertai kebijakan pendukung seperti pengadaan guru mulok atau pelatihan guru mulok, pengadaan buku-buku paket, atau ketentuan pengaturan guru mulok. Oleh sebab itu penerapan kurikulum mulok di sekolah terkesan terseok-seok, hidup tak mau matipun segan.
Pemecahan masalah
Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, kiranya perlu mempertimbangkan atau mengarus utamakan hal-hal berikut:
Pertama, tentunya perlu pengadaan guru mulok, paling tidak pelatihan terhadap guru yang sudah ada. Untuk memenuhi kebutuhan guru mulok maka LPTK seperti FKIP perlu membuka jurusan/program studi bahasa daerah. Upaya ini harus dibarengi dengan kebijakan pengadaan buku-buku mata pelajaran muatan lokal di daerah-daerah. Sistem guru kelas harus diganti dengan guru bidang studi seperti mata pelajaran agama dan olahraga. Jika di sebuah sekolah tidak terdapat guru mulok, maka dapat dilakukan sistem silang (lintas sekolah).
Kedua, kerja sama guru dengan para stakeholders terutama Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah perlu dikembangkan dan dimaksimalkan untuk memikirkan dan membicarakan berbagai masalah yang dihadapi dalam penetapan dan pengajaran muatan lokal. Hal ini harus diikuti dengan sikap tegas pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembinaan dan pengawasan.
Pelajaran budaya lokal, antara lain, dapat diajarkan materi adat-istiadat atau nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi dan bermanfaat bagi pembangunan sosial budaya misalnya aspek gotong royong adat sopan santun dan tata krama pergaulan, falsafah hidup dan ain sebagainya.
Materi sejarah lokal, antara lain, berupa perkembangan sejarah perjuangan menetang setiap bentuk penjajahan. Disini kita akan menemukan tokoh-tokoh pejuang yang selama ini masih diselimuti oleh kabut kegelapan. Tidak hanya itu, mungkin pula kita akan menemukan para pemikir, tokoh agama, pahlawan kemanusiaan dan lain sebagainya.
Pelajaran sejarah perjuangan akan membangkitan semangat patriotisme dan kebanggaan nasional. Dari materi sejarah lokal, seorang siswa dapat mengambil pelajaran (hikmah) sehingga kelak menjadi arif dan bijaksana.
Ketiga, pentingnya mempelajari budaya dan sejarah lokal ini telah diakui oleh para ahli. Misalnya sejarawan Sartono Kartodisardjo (1982) mengatakan bahwa seringkali hal-hal yang ada di tingkat nasional baru bisa dimengrti dengan lebih baik apabila kita mengerti dengan baik pula perkembangan di tingkat lokal. Hal-hal di tingkat yang lebih luas itu biasanya hanya memberikan gambaran dari pola-pola serta masalah-masalah umumnya, sedangkan situasinya yang lebih konkrit dan mendetail baru bisa diketahui melalui gambaran sejarah lokal? Dengan mempelajari budaya dan sejarah lokal, kita tidak hanya bisa memperkaya perbendaharaan kita tentang budaya dan sejarah nasional, tapi lebih penting lagi memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika sosiokultural dari masyarakat Indonesia yang majemuk ini secara rutin.
Dengan demikian kita makin menyadari pula bahwa ada berbagai corak penghadapan manusia dengan lingkungannya dan dengan kepentingan mempelajari sejarah.
Lebih tegas dikatakan oleh AB Lapian (1980) bahwa kepentingan mempelajari sejarah lokal, pertama-tama adalah untuk mengenal barbagai peristiwa sejarah di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia dengan lebih baik dan lebih bermakna. Kedua, untuk bisa mengadakan koreksi terhadap sejarah nasional. Ketiga, untuk memperluas pandangan tentang dunia Indonesia.
Dengan demikian pengajaran budaya dan sejarah lokal dalam jangka panjang akan memperjelas identitas dan jatidiri setiap daerah dengan segala kearifan lokalnya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam kerangka otonomi daerah, dalam arti bahwa daerah memang membutuhkan identitas, jati diri atau ciri khas (ideografis) yang berbeda dengan yang lain tetapi setara dalam satu kesatuan Negara republik Indonesia serta menghidari kecenderungan munculnya disintegrasi sosial.
Reposisi bahasa daerah
Selama kurang lebih 10 tahun penerapan mata pelajaran mulok di sekolah berbagai kendala yang dihadapi, utamanya yang berkaitan dengan aspek kebudayaan (bahasa daerah) dapat dilihat baik dari segi guru, buku paket, siswa, pemerintah maupun stakeholder. Kendala bisa diatasi dengan jalan pengadaan dan pelatihan guru mulok, membuka jurusan/program studi bahasa daerah, pengadaan buku pelajaran muatan lokal, perlunya sistem guru bidang studi dan sistem silang, kerja sama guru dengan stakeholders, sikap tegas pemerintah, perlunya perubahan istilah bahasa daerah menjadi bahasa lokal. Kalau perlu mereposisi mata pelajaran bahasa daerah menjadi mata pelajaran pilihan, bukan utama, diganti dengan mata pelajaran budaya lokal yang dapat diperkaya dengan materi sejarah lokal atau sebaliknya, sejarah lokal diperkaya dengan materi budaya lokal. (ali hadara)
Di dalam UU tersebut, mulok ditetapkan sebagai salah satu dari 10 mata pelajaran yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Akan tetapi bagaimana dan apa isi mulok tersebut akan ditentukan kemudian dalam ketentuan peraturan lainnya seperti PP, Kepmen atau SK Dirjen.
Dengan demikian masih terbuka peluang masukan kepada pihak penentu kebijakan dalam rangka penyusunan ini (substansi) muatan lokal dalam Kurikulum 2004. Karena Kurikulum 2004 masih dalam proses, maka pelaksanaan mulok di sekolah tetap berpedoman pada ketentuan Kurikulum 1994 serta peraturan lainnya.
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai masalah yang dihadapi selama kurang lebih 12 tahun penerapan mulok di sekolah,
khususnya dalam aspek kebudayaan (mata pelajaran bahasa daerah) serta mencoba mengajukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam penerapan mulok tersebut. Hasilnya diharapkan menjadi bahan saling tukar informasi dan diskusi bagi upaya pengembangan kurikulum muatan lokal, utamanya yang berkaitan dengan aspek kebudayaan di dalam kurikulum 2004.
Masalah yang dihadapi
Berdasarkan Kurikulum 1994 pihak depdikbud mengeluarkan kebijakan bahwa isi mulok pada masing-masing propinsi dapat berupa mata pelajaran kesenian, keterampilan (bercocok tanam, berternak, mengukir, mengayam, membantik, merajut, mengelas dan keterampilan lainnya), bahasa daerah dan budaya daerah, dan bahasa Inggris untuk SD.
Penentuannya dikaitkan dengan ketersediaan tenaga pengajar, buku pelajaran dan sumber belajar lainnya serta sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Isinya ditentukan oleh daerah, dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat informasi, saran dan masukan dari pemerintah daerah/bappeda, para tokoh masyarakat dan instansi terkait, baik tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten pada wilayah propinsi yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara menetapkan bahwa daerah (Tolaki, Muna dan Wolio)? sebagai muatan utama, sementara materi pilihan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah kecamatan, desa/kelurahan dan sekolah. Ketentuan ini termuat dalam SK Kakanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi tenggara No. 001/123/I/1994, tanggal 2 April 1994.
Selama kurang lebih 10 tahun penerapan mulok tersebut berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah, utamanya yang berkaitan dengan aspek kebudayaan (bahasa daerah) dapat dikemukakan sebagai berikut:
Pertama, dari segi guru yang tidak dipersiapkan sebelumnya sehingga berlaku prinsip tak ada rotan akarpun jadi. Biayanya guru? Mulok (bahsa daerah) adalah guru yang dapat berbahasa daerah berdasarkan pengalaman sehari-hari saja, tetapi tidak menguasai secara teoritis. Bagaimanapun juga bahasa daerah memiliki kaidah dan aturan tata bahasa yang harus dipelajari secara sungguh-sungguh oleh guru. Sistem guru kelas juga merupakan kendala tersendiri. Masalah yang muncul di dalam sistem guru kelas ini adalah bagaimana dengan guru yang tidak menguasai bahasa daerah. Akibatnya guru tidak serius mengajar, terkesan asal-asalan dan akal-akalan, apalagi mata pelajaran ini tidak di-ebtanas-kan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan buku paket serta buku-buku pendukung lainnya.
Kedua, dari segi siswa dengan latar belakang kultural yang berbeda-beda, terutama sekolah di kota dan daerah transmigrasi. Mereka kurang tertarik dengan pelajaran bahasa daerah karena merasa bukan bahasa ibunya, siswa merasa sebagai pendatang, atau tidak dibutuhkan dalam aktivitas kesehariannya. Pihak Kanwil Depdikbud Sulawesi Tenggara hanya mewajibkan tiga bahasa daerah (Tolaki, Muna dan Wolio) padahal di daerah ini terdapat sekitar 30 bahasa lokal yang tersebar di lima kabupaten dan dua kota, dimana antara satu bahasa dengan bahasa lainnya sangat berbeda. Di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau, misalnya, terdapat lebih dari 20 bahasa lokal, namun hanya satu bahasa yang wajib dipelajari, yaitu bahasa Wolio. Ini menjadi masalah besar bagi sekolah yang tak satupun gurunya mengerti bahasa Wolio, apalagi mengajarnya.
Di kota kendalanya lebih rumit lagi, latar belakang etnik siswa di kota beranekaragam dan populasinya hampir seimbang. Artinya, tidak ada yang dominan, lantas bahasa daerah apa yang harus diajarkan. Demikian pula sekolah-sekolah di daerah transmigrasi yang umumnya berasal dari Jawa dan Bali, perlukan mereka belajar bahasa daerah lain.
Ketiga, Pemerintah pun menerapkan kebijakan 'setengah hati' kurang tegas, tidak disertai kebijakan pendukung seperti pengadaan guru mulok atau pelatihan guru mulok, pengadaan buku-buku paket, atau ketentuan pengaturan guru mulok. Oleh sebab itu penerapan kurikulum mulok di sekolah terkesan terseok-seok, hidup tak mau matipun segan.
Pemecahan masalah
Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, kiranya perlu mempertimbangkan atau mengarus utamakan hal-hal berikut:
Pertama, tentunya perlu pengadaan guru mulok, paling tidak pelatihan terhadap guru yang sudah ada. Untuk memenuhi kebutuhan guru mulok maka LPTK seperti FKIP perlu membuka jurusan/program studi bahasa daerah. Upaya ini harus dibarengi dengan kebijakan pengadaan buku-buku mata pelajaran muatan lokal di daerah-daerah. Sistem guru kelas harus diganti dengan guru bidang studi seperti mata pelajaran agama dan olahraga. Jika di sebuah sekolah tidak terdapat guru mulok, maka dapat dilakukan sistem silang (lintas sekolah).
Kedua, kerja sama guru dengan para stakeholders terutama Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah perlu dikembangkan dan dimaksimalkan untuk memikirkan dan membicarakan berbagai masalah yang dihadapi dalam penetapan dan pengajaran muatan lokal. Hal ini harus diikuti dengan sikap tegas pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembinaan dan pengawasan.
Pelajaran budaya lokal, antara lain, dapat diajarkan materi adat-istiadat atau nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi dan bermanfaat bagi pembangunan sosial budaya misalnya aspek gotong royong adat sopan santun dan tata krama pergaulan, falsafah hidup dan ain sebagainya.
Materi sejarah lokal, antara lain, berupa perkembangan sejarah perjuangan menetang setiap bentuk penjajahan. Disini kita akan menemukan tokoh-tokoh pejuang yang selama ini masih diselimuti oleh kabut kegelapan. Tidak hanya itu, mungkin pula kita akan menemukan para pemikir, tokoh agama, pahlawan kemanusiaan dan lain sebagainya.
Pelajaran sejarah perjuangan akan membangkitan semangat patriotisme dan kebanggaan nasional. Dari materi sejarah lokal, seorang siswa dapat mengambil pelajaran (hikmah) sehingga kelak menjadi arif dan bijaksana.
Ketiga, pentingnya mempelajari budaya dan sejarah lokal ini telah diakui oleh para ahli. Misalnya sejarawan Sartono Kartodisardjo (1982) mengatakan bahwa seringkali hal-hal yang ada di tingkat nasional baru bisa dimengrti dengan lebih baik apabila kita mengerti dengan baik pula perkembangan di tingkat lokal. Hal-hal di tingkat yang lebih luas itu biasanya hanya memberikan gambaran dari pola-pola serta masalah-masalah umumnya, sedangkan situasinya yang lebih konkrit dan mendetail baru bisa diketahui melalui gambaran sejarah lokal? Dengan mempelajari budaya dan sejarah lokal, kita tidak hanya bisa memperkaya perbendaharaan kita tentang budaya dan sejarah nasional, tapi lebih penting lagi memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika sosiokultural dari masyarakat Indonesia yang majemuk ini secara rutin.
Dengan demikian kita makin menyadari pula bahwa ada berbagai corak penghadapan manusia dengan lingkungannya dan dengan kepentingan mempelajari sejarah.
Lebih tegas dikatakan oleh AB Lapian (1980) bahwa kepentingan mempelajari sejarah lokal, pertama-tama adalah untuk mengenal barbagai peristiwa sejarah di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia dengan lebih baik dan lebih bermakna. Kedua, untuk bisa mengadakan koreksi terhadap sejarah nasional. Ketiga, untuk memperluas pandangan tentang dunia Indonesia.
Dengan demikian pengajaran budaya dan sejarah lokal dalam jangka panjang akan memperjelas identitas dan jatidiri setiap daerah dengan segala kearifan lokalnya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam kerangka otonomi daerah, dalam arti bahwa daerah memang membutuhkan identitas, jati diri atau ciri khas (ideografis) yang berbeda dengan yang lain tetapi setara dalam satu kesatuan Negara republik Indonesia serta menghidari kecenderungan munculnya disintegrasi sosial.
Reposisi bahasa daerah
Selama kurang lebih 10 tahun penerapan mata pelajaran mulok di sekolah berbagai kendala yang dihadapi, utamanya yang berkaitan dengan aspek kebudayaan (bahasa daerah) dapat dilihat baik dari segi guru, buku paket, siswa, pemerintah maupun stakeholder. Kendala bisa diatasi dengan jalan pengadaan dan pelatihan guru mulok, membuka jurusan/program studi bahasa daerah, pengadaan buku pelajaran muatan lokal, perlunya sistem guru bidang studi dan sistem silang, kerja sama guru dengan stakeholders, sikap tegas pemerintah, perlunya perubahan istilah bahasa daerah menjadi bahasa lokal. Kalau perlu mereposisi mata pelajaran bahasa daerah menjadi mata pelajaran pilihan, bukan utama, diganti dengan mata pelajaran budaya lokal yang dapat diperkaya dengan materi sejarah lokal atau sebaliknya, sejarah lokal diperkaya dengan materi budaya lokal. (ali hadara)

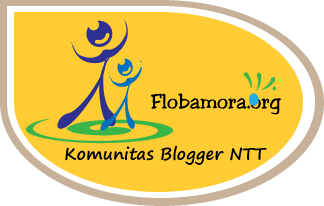






Tidak ada komentar:
Posting Komentar