SPIRIT NTT/WWW.BURUNG.ORG
Hutan Mbeliling
Spirit NTT, 8-14 Juni 2009
SIANG itu terik matahari seakan menghunjam jalanan semi aspal menuju desa di kaki Gunung Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Diselingi perbincangan ringan sembari berjalan kaki, penulis bersama rekan asli Sumba, Samuel Rabenak dan Karel, warga Desa Liang Dara berniat sowan ke rumah Tetua Adat Desa Cecar, Kecamatan Sano Nggoang.
Dalam bahasa Manggarai Tetua Adat disebut Tua Golo. Golo artinya gunung atau pegunungan. "Neka rabo, kraeng," sapa seorang pemuda tanggung menghentikan langkah kaki kami bertiga. Rupanya, pemuda itu salah seorang kerabat Karel yang berdomisili di Desa Cecar. Nekarabo, karaeng sendiri artinya "jangan marah, tuan". Sapaan itu merupakan salam pembuka perbincangan dan rasa hormat kepada seseorang yang dianggap sebagai sahabat. "Di Manggarai Barat ini hampir setiap orang bila berpapasan selalu berucap itu," terang Karel.
Sungguh wujud komunikasi setara yang sulit dijumpai di kota besar. Kearifan lokal ini menjadi semangat yang masih terasa di kawasan hutan Mbeliling, tempat hidup tiga jenis burung endemik Flores yakni kehicap flores (Monarcha sacerdotum), serindit flores (Loriculus flosculus), dan gagak flores (Corvus florensis).
Seusai saling bersapa, perjalanan berlanjut. Pada sebuah tanjakan, beberapa bocah seraya berkecumik lirih mengikuti langkah kaki kami. Ternyata mereka tertarik pada peralatan lapangan berupa binokuler yang ditenteng Karel dan handycam yang tergantung di bahu Samuel. "Itu rumah Tua Golo Cecar," tuding Karel sembari telunjuknya mengarah pada sebuah bangunan dari papan kayu yang ditopang tembok tanpa cat.
Bertiga kami masuki ruang tamu rumah Tua Golo. "Silakan masuk. Neka rabo kraeng. Beginilah tempat saya ini. Sederhana tapi teduh buat berlindung dari terik matahari di luar," kata lelaki yang pernah menjabat Kepala Desa itu. Seraya ulurkan tangan bersalaman, dia mengenalkan diri sebagai Yoseph Daru.
Suasana rumah lelaki berusia 65 tahun ini, hampir di luar bayangan penulis. Tadinya saya pikir rumah kepala suku atau tetua adat cukup mentereng bila dibandingkan warga lain. Ternyata keliru sangka. Rumah Yoseph tak jauh berbeda dengan hunian tetangga samping kiri-kanan. Aura sederhana khas masyarakat desa bertipikal paguyuban begitu kental meruap.
Sesaat sebelum punggung bersandar kursi, beberapa kerabat sang Tua Golo yang sedang bercengkerama di ruang tengah dan dapur bergegas ikut merubung tamu, bersalam-salaman mengenalkan identitas.
Apa sebenarnya peran Tua Golo dalam keseharian hidup masyarakat Manggarai Barat? Pertanyaan itu segera bergayung sambut jawaban. "Saya berkewajiban mengatur hidup masyarakat agar tidak melanggar kesusilaan, menjaga keindahan, dan ketertiban kampung. Kalau saya Tua Golo Cecar, berarti kewenangan saya hanya di desa ini. Tidak berhak mencampuri ulayat desa lain," pungkas Yoseph.
Wilayah kekuasaan Tua Golo, menurut Yoseph, selalu ditandai tapal batas berwujud batu atau sebatang pohon yang tidak boleh ditebang warga desa yang saling berbatasan.
Hak bagi tanah
Pada masyarakat adat yang memegang teguh tradisi secara temurun, posisi, fungsi, dan peran sosial Tua Golo tidak serta-merta dapat diabaikan. Tradisi sebagai nilai-nilai penjaga harmonisasi kehidupan antarwarga, sedikit banyak telah sublim. Menyatu dengan perilaku, cara pandang , dan etika seorang individu. Pola pikir inilah yang mengemuka dalam forum warga Manggarai Barat yang diadakan Burung Indonesia (1-2 Oktober 2007 lalu) di Labuan Bajo. Warga peserta sarasehan itu menamakannya nempung cama atau kesepakatan bersama antarmasyarakat desa.
Mereka meminta agar Tua Golo dilibatkan dalam pengelolaan hutan Mbeliling secara berkelanjutan. Tua Golo menjadi salah satu wakil masyarakat selain lembaga eksekutif yang diwakili Dinas Kehutanan, legislatif, dan lembaga sosial masyarakat. Mengapa Tua Golo harus ada di wadah nempung cama? Sebab, Tua Golo mengetahui situasi, kondisi di sekitar wilayahnya, mengetahui letak tapal batas hutan dan desa, memiliki hak ulayat, memiliki hak untuk membagi tanah, dan mempunyai kemampuan menyelesaikan konflik di tingkat masyarakat adat.
"Seseorang yang meminta lahan tidak bisa asal dan langsung diberi. Harus melalui tata cara adat tertentu. Selain itu, jika ada warga yang membuka ladang di kawasan hutan, Tua Golo akan melapor pada Dinas Kehutanan. Tua Golo tidak mempunyai hak menangkap orang yang memotong kayu atau membuka lahan tanpa izin," jelas Yoseph yang menjadi Kepala Desa Cecar dari 1968 hingga 1978 ini.
Sejak 1978, Yoseph Daru dipilih masyarakat Desa Cecar menjadi Tua Golo. Seiring perkembangan zaman, pola pewarisan Tua Golo juga mengalami pergeseran. Sebelumnya Tua Golo diwariskan secara turun-temurun, tetapi Yoseph terpilih dari keinginan dan aspirasi warga desa Cecar.
Prosesi adat
Lelaki lebih setengah abad yang masih tegas dan kekar untuk ukuran seusianya itu menerangkan, setiap orang yang tidak memiliki lahan namun ingin membuka ladang wajib menjalani prosesi adat. Orang itu harus bicara pada Tua Ame atau orangtuanya yang akan menyampaikan keinginannya kepada Tua Golo. Kemudian Tua Golo memberi perintah kepada wakilnya yang disebut Punggawa untuk diteruskan kepada Tua Batu, penanggungjawab adat untuk urusan tanah. Tua Batu lantas melihat lokasi dan jika tak ada masalah menyangkut riwayat tanah bersangkutan, segera dilaksanakan tancap batu atau kayu dan sembelih ayam. Tanah yang diminta itupun dibuatkan surat oleh kepala desa.
Sebelum diolah menjadi ladang, lahan yang biasanya ditumbuhi ilalang itu biasanya dibakar terlebih dahulu. Bila tanah telah diolah menjadi sawah maupun kebun, si penggarap akan dikenai pajak bumi. Dijelaskan Yoseph, ia telah melaksanakan pemetaan tanah ulayat, dan hasilnya telah diserahkan ke pemerintah daerah.
Bagaimana kalau tanah itu akan dijual? "Tanah ini bisa dijual dengan saksi Tua Golo. Kalau Tua Golo tidak turun tangan, tidak akan ada yang berani menjual tanah itu. Namun, setelah uang didapat si penjual, sepenuhnya uang tersebut hak milik pribadinya," tandas Yoseph.
Sementara itu, pendatang yang ingin memiliki tanah di Manggarai Barat menjalani proses yang berbeda. Pertama-tama, Tua Golo akan memanggil Punggawa, Tua Batu, Tua Ame, dan masyarakat lain sebagai saksi dalam wadah nempung capa. Pendatang datang ke forum sambil membawa sopi, yaitu minuman lokal yang jadi tanda persahabatan serta hidangan lainnya. Apabila mayoritas warga menyetujui, keinginan `memiliki' lahan dapat berjalan lancar. Namun jika warga menolak, pendatang itupun pulang dengan tangan hampa. Selain itu, sifat kepemilikan tanah bagi pendatang hanya hak kelola lahan. Artinya, bila orang tersebut ingin menjual tanahnya, seluruh uang hasil penjualan tanah wajib dikembalikan pada desa dinas dan adat. (praminto moehayat/burung indonesia/http://burung.org/detail_txt)
Hutan Mbeliling
Spirit NTT, 8-14 Juni 2009
SIANG itu terik matahari seakan menghunjam jalanan semi aspal menuju desa di kaki Gunung Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Diselingi perbincangan ringan sembari berjalan kaki, penulis bersama rekan asli Sumba, Samuel Rabenak dan Karel, warga Desa Liang Dara berniat sowan ke rumah Tetua Adat Desa Cecar, Kecamatan Sano Nggoang.
Dalam bahasa Manggarai Tetua Adat disebut Tua Golo. Golo artinya gunung atau pegunungan. "Neka rabo, kraeng," sapa seorang pemuda tanggung menghentikan langkah kaki kami bertiga. Rupanya, pemuda itu salah seorang kerabat Karel yang berdomisili di Desa Cecar. Nekarabo, karaeng sendiri artinya "jangan marah, tuan". Sapaan itu merupakan salam pembuka perbincangan dan rasa hormat kepada seseorang yang dianggap sebagai sahabat. "Di Manggarai Barat ini hampir setiap orang bila berpapasan selalu berucap itu," terang Karel.
Sungguh wujud komunikasi setara yang sulit dijumpai di kota besar. Kearifan lokal ini menjadi semangat yang masih terasa di kawasan hutan Mbeliling, tempat hidup tiga jenis burung endemik Flores yakni kehicap flores (Monarcha sacerdotum), serindit flores (Loriculus flosculus), dan gagak flores (Corvus florensis).
Seusai saling bersapa, perjalanan berlanjut. Pada sebuah tanjakan, beberapa bocah seraya berkecumik lirih mengikuti langkah kaki kami. Ternyata mereka tertarik pada peralatan lapangan berupa binokuler yang ditenteng Karel dan handycam yang tergantung di bahu Samuel. "Itu rumah Tua Golo Cecar," tuding Karel sembari telunjuknya mengarah pada sebuah bangunan dari papan kayu yang ditopang tembok tanpa cat.
Bertiga kami masuki ruang tamu rumah Tua Golo. "Silakan masuk. Neka rabo kraeng. Beginilah tempat saya ini. Sederhana tapi teduh buat berlindung dari terik matahari di luar," kata lelaki yang pernah menjabat Kepala Desa itu. Seraya ulurkan tangan bersalaman, dia mengenalkan diri sebagai Yoseph Daru.
Suasana rumah lelaki berusia 65 tahun ini, hampir di luar bayangan penulis. Tadinya saya pikir rumah kepala suku atau tetua adat cukup mentereng bila dibandingkan warga lain. Ternyata keliru sangka. Rumah Yoseph tak jauh berbeda dengan hunian tetangga samping kiri-kanan. Aura sederhana khas masyarakat desa bertipikal paguyuban begitu kental meruap.
Sesaat sebelum punggung bersandar kursi, beberapa kerabat sang Tua Golo yang sedang bercengkerama di ruang tengah dan dapur bergegas ikut merubung tamu, bersalam-salaman mengenalkan identitas.
Apa sebenarnya peran Tua Golo dalam keseharian hidup masyarakat Manggarai Barat? Pertanyaan itu segera bergayung sambut jawaban. "Saya berkewajiban mengatur hidup masyarakat agar tidak melanggar kesusilaan, menjaga keindahan, dan ketertiban kampung. Kalau saya Tua Golo Cecar, berarti kewenangan saya hanya di desa ini. Tidak berhak mencampuri ulayat desa lain," pungkas Yoseph.
Wilayah kekuasaan Tua Golo, menurut Yoseph, selalu ditandai tapal batas berwujud batu atau sebatang pohon yang tidak boleh ditebang warga desa yang saling berbatasan.
Hak bagi tanah
Pada masyarakat adat yang memegang teguh tradisi secara temurun, posisi, fungsi, dan peran sosial Tua Golo tidak serta-merta dapat diabaikan. Tradisi sebagai nilai-nilai penjaga harmonisasi kehidupan antarwarga, sedikit banyak telah sublim. Menyatu dengan perilaku, cara pandang , dan etika seorang individu. Pola pikir inilah yang mengemuka dalam forum warga Manggarai Barat yang diadakan Burung Indonesia (1-2 Oktober 2007 lalu) di Labuan Bajo. Warga peserta sarasehan itu menamakannya nempung cama atau kesepakatan bersama antarmasyarakat desa.
Mereka meminta agar Tua Golo dilibatkan dalam pengelolaan hutan Mbeliling secara berkelanjutan. Tua Golo menjadi salah satu wakil masyarakat selain lembaga eksekutif yang diwakili Dinas Kehutanan, legislatif, dan lembaga sosial masyarakat. Mengapa Tua Golo harus ada di wadah nempung cama? Sebab, Tua Golo mengetahui situasi, kondisi di sekitar wilayahnya, mengetahui letak tapal batas hutan dan desa, memiliki hak ulayat, memiliki hak untuk membagi tanah, dan mempunyai kemampuan menyelesaikan konflik di tingkat masyarakat adat.
"Seseorang yang meminta lahan tidak bisa asal dan langsung diberi. Harus melalui tata cara adat tertentu. Selain itu, jika ada warga yang membuka ladang di kawasan hutan, Tua Golo akan melapor pada Dinas Kehutanan. Tua Golo tidak mempunyai hak menangkap orang yang memotong kayu atau membuka lahan tanpa izin," jelas Yoseph yang menjadi Kepala Desa Cecar dari 1968 hingga 1978 ini.
Sejak 1978, Yoseph Daru dipilih masyarakat Desa Cecar menjadi Tua Golo. Seiring perkembangan zaman, pola pewarisan Tua Golo juga mengalami pergeseran. Sebelumnya Tua Golo diwariskan secara turun-temurun, tetapi Yoseph terpilih dari keinginan dan aspirasi warga desa Cecar.
Prosesi adat
Lelaki lebih setengah abad yang masih tegas dan kekar untuk ukuran seusianya itu menerangkan, setiap orang yang tidak memiliki lahan namun ingin membuka ladang wajib menjalani prosesi adat. Orang itu harus bicara pada Tua Ame atau orangtuanya yang akan menyampaikan keinginannya kepada Tua Golo. Kemudian Tua Golo memberi perintah kepada wakilnya yang disebut Punggawa untuk diteruskan kepada Tua Batu, penanggungjawab adat untuk urusan tanah. Tua Batu lantas melihat lokasi dan jika tak ada masalah menyangkut riwayat tanah bersangkutan, segera dilaksanakan tancap batu atau kayu dan sembelih ayam. Tanah yang diminta itupun dibuatkan surat oleh kepala desa.
Sebelum diolah menjadi ladang, lahan yang biasanya ditumbuhi ilalang itu biasanya dibakar terlebih dahulu. Bila tanah telah diolah menjadi sawah maupun kebun, si penggarap akan dikenai pajak bumi. Dijelaskan Yoseph, ia telah melaksanakan pemetaan tanah ulayat, dan hasilnya telah diserahkan ke pemerintah daerah.
Bagaimana kalau tanah itu akan dijual? "Tanah ini bisa dijual dengan saksi Tua Golo. Kalau Tua Golo tidak turun tangan, tidak akan ada yang berani menjual tanah itu. Namun, setelah uang didapat si penjual, sepenuhnya uang tersebut hak milik pribadinya," tandas Yoseph.
Sementara itu, pendatang yang ingin memiliki tanah di Manggarai Barat menjalani proses yang berbeda. Pertama-tama, Tua Golo akan memanggil Punggawa, Tua Batu, Tua Ame, dan masyarakat lain sebagai saksi dalam wadah nempung capa. Pendatang datang ke forum sambil membawa sopi, yaitu minuman lokal yang jadi tanda persahabatan serta hidangan lainnya. Apabila mayoritas warga menyetujui, keinginan `memiliki' lahan dapat berjalan lancar. Namun jika warga menolak, pendatang itupun pulang dengan tangan hampa. Selain itu, sifat kepemilikan tanah bagi pendatang hanya hak kelola lahan. Artinya, bila orang tersebut ingin menjual tanahnya, seluruh uang hasil penjualan tanah wajib dikembalikan pada desa dinas dan adat. (praminto moehayat/burung indonesia/http://burung.org/detail_txt)

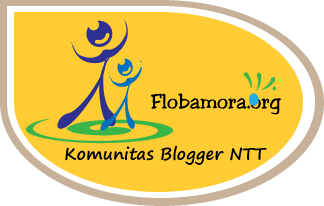







Tidak ada komentar:
Posting Komentar